SILOGISME DALAM PANDANGAN CENDEKIAWAN ISLAM
DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS UTS MATA KULIAH
FILSAFAT ILMU
Dosen Pengampu Ahmad Mu’is,S.Ag, MA
Disusun oleh :
MOHAMAD BASTOMI
(11510131)
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
APRIL 2012
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kami masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyusun makalah dengan judul “SILOGISME DALAM FILSAFAT ISLAM” guna memenuhi tugas UTS Semester dua.
Tersusunnya makalah ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:
- Bapak Ahmad Mu’is,S.Ag, MA selaku dosen pengampu mata kuliah FILSAFAT ILMU yang memberikan arahan dan masukan dalam makalah ini.
- Serta semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini yang tidak mingkin kami sebutkan satu persatu.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempuran. Demi tercapainya suau kesempurnaan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.
Demikaian hal yang dapat kami sampaikan, kami berharap makalah ini dapat berguna bagi pembaca.
Malang, 14 April 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
- Latar Belakang Pembahasan 1
- Rumusan Masalah 2
- Tujuan Pembahasan 2
BAB II SILOGISME
- Pengertian Silogisme 3
- Macam-macam silogisme 5
- Hukum-hukum Silogisme 7
- Hukum-hukum Premis dalam Silogisme 8
- Penarikan Simpulan 9
6. Pendapat Al-Farabi terhadap silogisme 10
7. Kritik IBN TAIMIYAH terhadap Silogisme 14
BAB III PENUTUP
- Kesimpulan 24
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembahasan
Filsafat bagi sebagian orang Islam seolah racun dalam darah, yang harus dinetralisir, bahkan kalau perlu dibuang anggota tubuh yang terlancur terjangkiti.Hal ini terasa wajar bila ditilik dari perjalanan panjang sejarah perkembangan filsafat pada mulanya.Proses persenyawaan filsafat dengan para pemikir Islam baru terasa kental setelah al-Kindi, al-Farabi, al-Ghazali dan tokoh-tokoh Islam lainnya meletakkan filsafat sebagai salah satu instrument berfikir runtut untuk mencapai tingkat pemahaman tertentu dari sebuah masalah yang berkembang.
Pola berfikir kritis analitis sangat berhubungan dengan metode perfikir runtut yang logic.Persenyawaan pola pandang yang baik dengan akurasi data yang sempurna, dan analitik sangat didukung oleh Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi akal-pikiran sebagai salah satu alat untuk mencapai kebenaran yang dituju.
Berangkat dari sedikitnya ummat Islam yang menyadari, bahwa berpola pikir logic sangat menopang pemahaman keberagamaan yang dijalani, sehingga banyak ditemukan di lapangan berbagai keputusan individu atau kelompok yang mengatasnamakan agama seakan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat ilmiah.Maka tidak aneh bila berbagai keputusan tersebut menjadi anti tesis bagi kebenaran yang diyakini oleh mereka yang melemparkan ide di tengah masyarakat ilmiah tersebut, namun tidak memiliki landasan dan kerangka berfikir kritis, analitik dan ilmiah sebagaimana yang dimaui dalam pembelajaran logika terlebih silogisme.
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi akal pikiran benar-benar menganjurkan ummatnya untuk melakukan apapun dengan landasan ilmiah yang memiliki akurasi data yang baik, dan benar.Sehingga ditemukan pemahaman “BAL” dalam bertindak; Benar-Akurat-Lengkap.
Filsafat melalui salah satu cabangnya, memberikan jalan keluarnya dengan istilah logika yang juga banyak dikenal di dunia Islam dengan istilah mantiq, yang juga memiliki cabang alat berfikir runtut yang dikenal dengan silogisme.
Penulis berupaya menawarkan dalam pemahaman masyarakat ilmiah untuk memiliki pola berfikir yang baik sebagaimana disebutkan di atas dengan membahas masalah silogisme dan manfaatnya dalam kehidupan.
1.2 Rumusan Masalah
Untuk mencapai penulisan karya ilmiah yang benar, maka penulis meletakkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
- Apakah yang dimaksud dengan silogisme?
- Apakah cabang-cabang dan hukum-hukum silogisme?
- Bagaimanakah pendapat ilmuan muslim terhadap silogisme ?
1.3 Tujuan Pembahasan
Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:
- Pengertian silogisme.
- Cabang-cabang dan hukum-hukum silogisme.
- Kritikan ilmuan muslim trhadap silogisme.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN SILOGISME (Qiyas)
Sebuah silogisme (bahasa Yunani: συλλογισμός – syllogismos – “kesimpulan,” “inferensi”) atau banding logis adalah jenis argumen logis di mana satu proposisi (kesimpulan) yang disimpulkan dari dua orang lain (tempat) dari suatu bentuk tertentu, yaitu kategori proposisi.[[1]] Dalam bahasa Arab, silogisme biasanya diterjemahkan dengan al-qiyas atau al-qiyasal-jam’i yang mengacu pada makna asal, yaitu mengumpulkan. Dalam aturan logika, silogisme biasanya digambarkan sebagai suatu bentuk penalaran yang tersusun atas tiga unsur : subjek (maudlu’), predikat (mahmul) dan relasi diantara keduanya. Menurut Aristoteles, seperti ditulis Jabiri, penarikan kesimpulan silogisme harus memenuhi beberapa syarat, (1) mengetahui latar belakang dari penyusunan premis (2) adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan, (3) kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar, sehingga tidak mungkin menimbulkan kebenaran atau kepastian lain.[[2]]
1. Dalam Bahasan Mantiq Silogisme atau Qiyas diartikan sebagai kumpulan dari beberapa qadhiyyah yang berkaitan yang jika benar, maka dengan sendirinya (li dzatihi) akan menghasilkan qadhiyyah yang lain (baru).[[3]]
Beberapa macam hujjah (argumentasi). Manusia disaat ingin mengetahui hal-hal yang majhul, maka terdapat tiga cara untuk mengetahuinya(Husein Al-Kaff. 1999):
1. Pengetahuan dari juz’i ke juz’i yang lain. Argumenatsi ini sifatnya horisontal, dari sebuah titik yang parsial ke titik parsial lainnya. Argumentasi ini disebut tamtsil (analogi).
2. Pengetahuan dari juz’i ke kulli. Atau dengan kata lain, dari khusus ke umum (menggeneralisasi yang parsial) Argumentasi ini bersifat vertikal, dan disebut istiqra’ (induksi).
3. Pengetahuan dari kulli ke juz’i. Atau dengan kata lain, dari umum ke khusus. Argumentasi ini disebut qiyas (silogisme).
Sesuai dengan definisi qiyas di atas, satu qadhiyyah atau beberapa qadhiyyah yang tidak dikaitkan antara satu dengan yang lain tidak akan menghasilkan qadhiyyah baru. Jadi untuk memberikan hasil (konklusi) diperlukan beberapa qadhiyyah yang saling berkaitan. Dan itulah yang namanya qiyas. (Husein Al-Kaff. 1999)
- Pengertian Silogisme dalam buku “Sebelum Analytics “, Aristoteles mendefinisikan silogisme sebagai “sebuah wacana di mana, hal-hal tertentu yang telah seharusnya, sesuatu yang berbeda dari hal-hal seharusnya hasil dari kebutuhan karena hal-hal ini begitu.” (24b18–20) (24b18-20)
Meskipun definisi yang sangat umum ini, ia membatasi diri pertama silogisme kategoris (dan kemudian untuk modal silogisme). Silogisme berada pada inti tradisional penalaran deduktif, dimana fakta ditentukan dengan menggabungkan laporan yang ada, berbeda dengan penalaran induktif dimana fakta ditentukan oleh pengamatan berulang. Silogisme digantikan oleh orde pertama logika predikat mengikuti karya Gottlob Frege , khususnya Nya Begriffsschrif (Konsep Script) (1879)
Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan, dari dua macam keputusan (yang mengandung unsur yang sama, dan salah satunya harus universal) suatu keputusan yang ketiga, yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahuluinya. (wikipedia.org/wiki/Proposition-Silogisme)
Maka bisa disimpulkan, bahwa silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif, yang disusun dari pernyataan dan konklusi (kesimpulan). Penalarannya bertolak dari pernyataan bersifat umum menuju pada pernyataan/simpulan khusus.
Absah dan Benar
Dalam membicarakan silogisme mengenal dua istilah yaitu absah dan benar.
- Absah (valid) berkaitan dengan prosedur apakah pengambilan konklusi sesuai dengan patokan atau tidak. Dikatakan valid apabila sesuai dengan patokan dan tidak valid bila sebaliknya.
- Benar berkaitan dengan:
- Proposisi dalam silogisme itu.
- Didukung atau sesuai dengan fakta atau tidak. Bila sesuai fakta, proposisi itu benar, bila tidak ia salah.
Keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan satuan yang tidak bisa dipisahkan, untuk mendapatkan yang sah dan benar. Hanya konklusi dari premis yang benar prosedur yang sah konklusi itu dapat diakui.
2.2. Macam-Macam Qiyas
1.Qiyas Iqtirani
Qiyas iqtirani adalah qiyas yang mawdhu' dan mahmul natijahnya berada secara terpisah pada dua muqaddimah. Contoh: "Kunci itu besi" dan "setiap besi akan memuai jika dipanaskan", maka "kunci itu akan memuai jika dipanaskan". Qiyas ini terdiri dari tiga qadhiyyah; [1] Kunci itu besi, [2] setiap besi akan memuai jika dipanaskan dan [3] kunci itu akan memuai jika dipanaskan.
Qadhiyyah pertama disebut muqaddimah shugra (premis minor), qadhiyyah kedua disebut muqaddimah kubra (premis mayor) dan yang ketiga adalah natijah (konklusi).
Natijah merupakan gabungan dari mawdhu' dan mahmul yang sudah tercantum pada dua muqaddimah, yakni, "kunci" (mawdhu') dan "akan memuai jika dipanaskan" (mahmul). Sedangkan "besi" sebagai hadawshat.
Yang paling berperan dalam qiyas adalah penghubung antara mawdhu' muqadimah shugra dengan mahmul muqaddimah kubra. Penghubung itu disebut had awsath. Had awsath harus berada pada kedua muqaddimah (shugra dan kubra) tetapi tidaktecantumdalamnatijah.(Lihatcontoh,pen).
a. Empat Bentuk Qiyas Iqtirani
Qiyas iqtirani kalau dilihat dari letak kedudukan had awsath-nya pada muqaddimah shugra dan kubra mempunyai empat bentuk:
Syakl Awwal adalah Qiyas yang had awsth-nya menjadi mahmul pada muqaddimah shugra dan menjadi mawdhu' pada muqaddimah kubra. Misalnya, "Setiap Nabi itu makshum", dan "setiap orang makshum adalah teladan yang baik", maka "setiap nabi adalah teladan yang baik". "Makshum" adalah had awsath, yang menjadi mahmul pada muqaddimah shugra dan menjadi mawdhu' pada muqaddimah kubra. Syarat-syaratsyaklawwal.
Syakl awwal akan menghasilkan natijah yang badihi (jelas dan pasti) jika memenuhi dua syarat berikut ini:
- Muqaddimah shugra harus mujabah.
- Muqaddimah kubra harus kulliyah.
Syakl Kedua adalah Qiyas yang had awshat-nya menjadi mahmul pada kedua muqaddimah-nya. Misalnya, "Setiap nabi makshum", dan "tidak satupun pendosa itu makshum", maka "tidak satu pun dari nabi itu pendosa".
Syarat-syarat syakl kedua.
- 1.Kedua muqaddimah harus berbeda dalam kualitasnya (kaif, yakni mujabah dan salibah).
- Muqaddimah kubra harus kulliyyah.
Syakl Ketiga adalah Qiyas yang had awshat-nya menjadi mawdhu' pada kedua muqaddimahnya. Misalnya, "Setiap nabi makshum", dan "sebagian nabi adalah imam", maka"sebagianorangmakshumadalahimam".
Syarat-syarat Syakl ketiga.
- Muqaddimah sughra harus mujabah.
- Salah satu dari kedua muqaddimah harus kulliyyah.
Syakal Keempat adalah Qiyas yang had awsath-nya menjadi mawdhu' pada muqaddimah shugra dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubra (kebalikan dari syakl awwal.)
Syarat-syarat Syakl keempat.
- Kedua muqaddimahnya harus mujabah.
- Muqaddimah shugra harus kulliyyah. Atau
- Kedua muqaddimahnya harus berbeda kualitasnya (kaif)
- Salah satu dari keduanya harus kulliyyah.
Catatan: Menurut para mantiqiyyin, bentuk qiyas iqtirani yang badihi (jelas sekali) adalah yang pertama sedangkan yang kedua dan ketiga membutuhkan pemikiran. Adapun yang keempat sangat sulit diterima oleh pikiran. Oleh karena itu Aristoteles sebagai penyusun mantiq yang pertama tidak mencantumkan bentuk yang keempat.
2.Qiyas Istitsna'i
Berbeda dengan qiyas iqtirani, qiyas ini terbentuk dari qadhiyyah syarthiyyah dan qadhiyyah hamliyyah. Misalnya, "Jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah". Penjelasannya: "Jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat" adalah qadhiyyah syarthiyyah yang terdiri dari muqaddam dan tali (lihat definisi qadhiyyah syarthiyyah), dan "Dia mempunyai mukjizat" adalah qadhiyyah hamliyyah. Sedangkan "maka dia mempunyai mukjizat" adalah natijah. Dinamakan istitsna'i karena terdapat kata " tetapi", atau "oleh karena". Macam-Macam Qiyas istitsna'i (silogisme) Ada empat macam qiyas istitsna'i: Muqaddam positif dan tali positif. Misalnya, "Jika Muhammad utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi Muhammad mempunyai mukjizat berarti Dia utusan Allah". Muqaddam negatif dan tali positif. Misalnya, "Jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Tetapi bumi tidak hancur, berarti Tuhan satu (tidak tidak satu)".
Tali negatif dan muqaddam negatif. Misalnya, "Jika Muhammad bukan nabi, maka dia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi dia mempunyai mukjizat, berarti dia Nabi (bukan bukan nabi)". Tali negative dan muqaddam positif. Misalnya, "Jika Fir'aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa. Tetapi dia binasa, berarti dia bukan Tuhan"
2.3 HUKUM-HUKUM SILOGISME
Supaya silogisme dapat merupakan jalan pikiran yang baik ada beberapa hukum dalam silogisme. Hukum tersebtu bukanlah buatan para ahli-pikir, tapi hanya dirumuskan oleh para ahli itu. Di bawah ini hukum-hukum yang menyangkut term-term antara lain:
- Hukum pertama. Silogisme tidak boleh lebih atau kurang dari tiga term. Kurang dari tiga term berarti bukan silogisme. Jika sekiranya ada empat term, apakah yang akan menjadi pokok perbandingan, tidak mungkinlah orang membandingkan dua hal denga dua hal pula, dan lenyaplah dasar perbandingan.
- Hukum kedua. Term antara atau tengah (medium) tidak boleh masuk (terdapat) dalam kesimpulan. Term medium hanya dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan dengan term-term. Perbadingan ini terjadi dalam premis-premis. Karena itu term medium hanya berguna dalam premis-premis saja.
- Hukum ketiga. Wilayah term dalam konklusi tidak boleh lebih luas dari wilayah term itu dalam premis. Hukum ini merupakan peringatan, supaya dalam konklusi orang tidak melebih-lebihkan wilayah yang telah diajukan dalam premis. Sering dalam praktek orang tahu juga, bahwa konklusi tidak benar, oleh karena tidak logis (tidak menurut aturan logika), tetapi tidak selalu mudah menunjuk, apa salahnya itu.
- Term antara (medium) harus sekurang-kurangnya satu kali universal. Jika term antara paticular, baik dalam premis mayor maupun dalam premis minor, mungkin saja term antara itu menunjukkan bagian-bagian yang berlainan dari seluruh luasnya. Kalau demikian term antara, tidak lagi berfungsi sebagai term antara, dan tidak lagi menghubungkan atau memisahkan subyek dengan predikat.
2.4 HUKUM-HUKUM PREMIS DALAM SILOGISME
Sedangkan hukum-hukum yang menyangkut premis-premis (keputusan-keputusan) antara lain: (Mundiri. 1994: 30-48)
- Jika kedua premis (mayor dan minor) positif, maka kesimpulannya harus positif juga.
- Kedua premis tidak boleh negatif, sebab term antara (medium) tidak lagi berfungsi sebagai penghubung atau pemisah subyek dengan predikat. Dalam silogisme sekurang-kurangnya subyek atau predikat harus dipersamakan oleh term antara (medium).
- Kedua premis tidak boleh particular. Sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Kalau tidak, berarti melanggar hukum pada bagian hukum-hukum term.
- Kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah. Keputusan particular adalah keputusan yang lemah dibandingkan dengan keputusan universal. Keputusan negatif adalah keputusan yang lemah dibandingkan dengan keputusan positif karena itu jika ada satu premis particular, maka kesimpulan harus particular. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Jika salah satu premis negatif dan particular, maka kesimpulannya harus negatif dan particular juga. Kalau tidak akan terjadi ketidak beresan lagi dalam kesimpulan.
PENARIKAN SIMPULAN
Penarik simpulan dengan silogisme dibedakan menjadi dua macam
- Menarik simpulan berdasarkan satu premis(pernyataan).
- Menarik Simpulan berdasarkan berdasarkan dua premis/pernyataan.
2.5 PENJABARAN SILOGISME BERDASARKAN KATEGORI
Silogisme Kategorik
Silogisme Katagorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan katagorik. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan dengan premis mayor (premis yang termnya menjadi predikat), dan premis minor (premis yang termnya menjadi subjek). Yang menghubungkan diantara kedua premis tersebut adalah term penengah (middle term). (Mundiri. 1994: 44)
Hukum-Hukum Silogisme Katagorik (Mundiri. 1994: 45-53).
- Dari dua premis yang sama-sama negatif, tidak menjadi kesimpulan apa pun, karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan diambil bila sedikitnya salah satu premis positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah.
- Paling tidak salah satu dari term penengah harus mencakup. Dari dua premis yang term penengahnya tidak tentu menghasilkan kesimpulan yang salah.
- Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis layor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna beda kesimpulan menjadi lain.
Silogisme Hipotesis
Adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi katagorik. (Arikunto, Suharsimi. 2006: 91)
- Hukum-Hukum Silogisme Hipotesis
Mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategorik. Tetapi yang penting di sini dalah menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. (Arikunto, Suharsimi. 2006: 92)
Silogisme Disyungtif
Adalah silogisme yang premis mayornya keputusan disyungtif sedangkan premis minornya kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor.Seperti pada silogisme hipotetik istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog bukan yang semestinya. (Arikunto, Suharsimi. 2006: 97)
Maka silogisme Jenis ini terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulannya akan menolak alternatif yang lain. (Arikunto, Suharsimi. 2006:99)
2.6 Pendapat Al-Farabi terhadap silogisme
Al-Farabi sendiri menggambarkan silogisme adalah suatu bentuk penalaran di mana dua proposisi yang disebut premis dirujukkan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah konklusi niscaya menyertainya.[[4]] Kedua proposisi yang tersebut masing-masing mempunyai unsur yang sama yang disebut term tengah (al-had al-ausath). Term tengah ini bisa menjadi subjek bagi premis yang satu dan menjadi predikat bagi premis lainnya, menjadi predikat bagi kedua premis, atau menjadi subjek bagi kedua premis. Karena itu, dikatakan ada tiga model atau figur silogisme sesuai dengan tiga posisi kemunculan term tengah dalam premis-premis suatu silogisme. Al-Farabi menyatakan bahwa silogisme model pertama, yaitu silogisme yang mana term tengah merupakan predikat satu premis dan subjek premis lainnya, adalah silogisme sempurna karena ia dapat dengan sendirinya menghasilkan putusan niscaya tanpa proses lain. Ini berbeda dengan dua model silogisme lainnya yang meski juga menghasilkan putusan niscaya tetapi masih harus didahului proses-proses lain agar didapatkan silogisme sempurna. Proses-proses ini yang dimaksud adalah dengan cara menambahkan satu proposisi atau lebih. Al-Farabi menyebutdua cara untuk membuat silogisme “tidak sempurna” menjadi silogisme sempurna sehingga keputusan yang dihasilkan menduduki posisi niscaya. (1) metode konversi (‘aks) di mana proposisi tambahan diambil dari apa yang telah ada secara implisit dalam premis-premis asal. (2) metode hipotesis atau esthesis (iftiradl) di mana proposisi tambahan dipasang sebagai hipotesis.[[5] ]
Selanjutnya berdasarkan materi dan kualitas premis-premis yang digunakan, al-farabi menyebut ada dua bentuk silogisme. Pertama, silogisme demonstratif (al-qiyas al-burhani). Silogisme demonstratif adalah suatu bentuk penalaran yang tersusun atas premis-premis yang benar, primerdan diperlukan. Premis yang benar, primerdan diperlukan adalah premis yang didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan primer (al-maqulat al-ula) atau premis-premis yang diturunkan melaluisilogisme yang valid (sah). Selain itu, al-Farabi juga menerima jenis-jenis pengetahuan indera sebagai premis silogisme demonstratif dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa ia harus dihasilkan dari objek-objek yang seantiasa sama (konstans) ketika diamati, di manapun dan kapanpun, baik pada masa lalu, sekarang atau yang datang, dan tidak ada silogisme lain yang menyimpulkan kebalikannya.[[6]] Syarat ini sejalan dengan konsep al-Farabi tentang keyakinan pasti dan keyakinan temporal seperti seperti yang dijelaskan di atas. Syarat ini juga sesuai dengan konsep pengetahuan al-Farabi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengetahuan yang benar dan sesngguhnya adalah yang berkaitan dengan objek tetap dan tidak berubah
Kedua, silogisme diaktelis (al-qiyas al-jadali), yaitu bentuk penalaran yang tersusun atas premis-premis yang hanya bersifat “mendekati keyakinan” (muqarib li al-yaqin), tidak sampai derajat meyakinkan (al-yaqin) seperti dalam penalaran demonstratif. Premis ini, menurut al-Farabi, sama posisi dan derajatnya dengan opini-opini yang secara umumnya diterima adalah statemen-statemen yang diakui oleh mayoritas masyarakat, atau oleh semua sarjana (‘uqala’), atau mayoritas mereka. Perbedaan antara premis yang meyakinkan dengan opini yang secara umum diterima adalah bahwa yang disebutkan kedua biasanya diakui hanya atas dasar keimanan atau kesaksian orang lain, tanpa uji rasional. Menurut al-Farabi, apa yang umumnya diterima tidak niscaya benar.[[7]]
Pembagian bentuk silogisme al-Farabi di atas mengingatkan kita pada aturan dalam logika modern. Dalam kajian logika modern, silogisme biasanya juga dibagi dalam dua bentuk : silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme kategoris adalah bentuk silogisme di mana premis-premisnya didasarkan atas data-data yang tidak terbantahkan, mutlak tidak tergantung dari suatu syarat; silogisme hipotesis adalah bentuk silogisme yang premis-premisnya tidak merupakan pernyataan mutlak melainkan tergantung pada sesuatu syarat.[[8]] Silogisme kategoris dapat disamakan dengan silogisme demonstratif (burhani) sedang silogisme hipotesis dapat disamakan dengan silogisme dialektelis (jadali).
Sementara itu, induksi (tashaffuh) dalam pengertian al-farabi adalah sebuah bentuk pegujian atas setiap contoh khusus yang tergolong dalam suatu subjek universal untuk menentukan apaka suatu perdikat atau penilaian yang dilakukan tentang hal tersebut berlaku secara universal atau tidak. Pada penelitian kuantitatif, metode induksi al-Farabi agaknya mirip dengan penelitian induksi yang bersifat uji teori. Pada kajian tentang pembentukan teori atau konsepsi ada perbedaan antara induksi ilmia al-Farabi dan induksi konvesional. Al-farabi sendiri tidak mengakui induksi konvesional sebagai sebuah bentuk penalaran yang handal karena dianggap tidak memberikan kepastian. Dalam pandangannya induksi konvesional sejajar dengan silogisme dialektis karena hanya memberikan kesimpulan pada tingkat mendekati keyakinan. [[9]]
Adapun retorika (al-khuthabi), adalah suatu bentuk penalaran yang didasarkan atas premis-premis yang kualitasnya hanya bersifat percaya semata (sukun al-nafs). Posisi dan derajat premis yang bersifat percaya semata ini setara denga opini yang diterima (al-maqbulat) dan berada di bawah opini yang umumnya diterima (al-masyhurat) karena ia tidak diakui oleh mayoritas masyarakat. Lebih dari itu, premis percaya semata bahkan hanya diterima oleh seorang individu atau paling banter dari sekelompok kecil orang, tanpa penyelidikan secara ilmiah apakah yang diterima tersebut benar adanya atau justru sebaliknya.[[10]]
Di samping tiga bentuk penalaran di atas, al-Farabi juga menyebutkan tentang puitik (al-syi’ri), yaitu suatu bentuk pemikiran yang didasarkan atas premis-premis berupa proposisi-proposisi yang dibyangkan. Maksudnya, makna-makna yang berkaitan dengan kata-kata yang digunakan dalam proposisi tersebut hanya merupakan tiruan-tiruan dari hal-hal yang ditunjukkan oleh kata-katanya. Menurut al-Farabi, puitik ini tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan bagi sebuah proses penalaran logis.[[11]]
Ketiga bentuk penalaran di atas, menurut al-Farabi, berbeda tingkat validitasnya sesuai dengan tingkat kualitas premis yang digunakan. Bentuk penalaran yang paling valid dan unggul adalah silogisme demonstratif karena premis yang digunakan adalah sesuatu yang meyakinkan, yaitu pengetahuan primer. Pengetahuan primer ini sendiri menempati rangking tertinggi dalam hierarki silogisme. Di bawahnya adalah silogisme diakletis, karena premis-premis yang digunakan hanya bertarap mendekati keyakinan, bukan yang meyakinkan seperti silogisme demonstratif. Materi premis silogisme dialektis berupa opini-opini yang secar umum diterima (al-masyhurat) biasanya diakui atas dasar keimanan atau kesaksian orang lain tanpa duiji rasional. Meski demikian, silogisme dialektis masih lebih unggul dibandingkan penalaran retorik, dan apalagi puitik, karena salah satu premis utama dalam penalaran retorik telah dibuang sehingga keputusan yang dihasilkan tidak meyakinkan, sedang puitik malah tidak memenuhi persyaratan sebuah aturan penalaran logis.
2.7 Kritik IBN TAIMIYAH terhadap Silogisme
Kritik Ibn Taimiyah terhadap silogisme Aristoteles terdiri dari dua aspek, aspek negatif dan aspek afirmatif. Berikut penjelasan kedua aspek tersebut :
1. Aspek Negatif
Dalam logika Aristoteles dinyatakan bahwa “suatu putusan tidak dapat diperoleh melainkan dengan silogisme”. Pernyataan ahli logika ini, kata Ibn Taimiyah adalah suatu proposisi negatif, dan pernyataan ini tidak dapat dipahami begitu saja, karena tidak dijelaskan alasan penegatifannya. Karena itu klaim mereka tidak berdasarkan atas dasar bukti yang jelas, bahkan ia merupakan suatu pernyataan tanpa ilmu. Padahal suatu ilmu tidak dapat menerima pernyataan negatif begitu saja. Karenanya, kata ibn Taimiyah, ia merupakan suatu pendapat yang tidak benar, kenapa suatu pernyataan tidak dapat diketahui kecuali sesuatu mesti dengan silogisme logis universal (al-qiyas al-manthiqy al-syumuly). Artinya, para ahli logika tidak mengemukakan alasan mereka, kenapa suatu pernyataan tidak dapat diketahui kecuali harus dengan silogisme.
Berikut ini adalah beberapa kritikan Ibn Taimiyah terhadap logika Aristoteles dari aspek negatif.
a. Kesimpulan tidak membutuhakan Term Penengah
Sebagaimana sudah disebutkan pada kritikan Ibn Taimiyah terhadap proposisi, adalah bahwa pembedaan para ahli logika antara proposisi aksiomatik dan teoretis spekulatif adalah persoalan yang relatif semata. Apa yang dianggap mudah atau aksiomatik bagi seseorang bisa sulit dan spekulatif bagi orang lain. Apa yang sukar dihasilkan oleh seseorang, dan harus dengan pengkajian yang mendalam dan dalam waktu yang lama, dapat merupakan hal yang mudah dan dihasilkan dalam waktu yang relatif pendek bagi orang lain.[[12]]
Menurut Ibn Taimiyah, sebenarnya dasar pembagian itu sama sekali tidak jelas, mengingat betapa secara radikal orang-orang berbeda daya nalar dan daya tangkapnya. Maka, ada orang yang karena ketajaman daya intuisinya dan nalarnya dengan mudah dapat mengetahui term penengah, yang kepadanya tergantung keabsahan silogisme.
Untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah pernyataan aksiomatik kita tidak perlu menyusun silogisme yang terdiri dari term penengah, tetapi cukup dengan memahami subjek dan predikat dari pernyataan itu. Dengan demikian, kita dapat sampai kepada pernyataan kesimpulan tanpa membutuhkan term penengah dalam bentuk silogisme.[[13]]
Adapun pada proposisi yang bukan teoretis spekulatif, maka ketergantungan kepada term penengah untuk mengetahui suatu pernyataan kesimpulan adalah relatif. Bagi sebagian orang membutuhkan term penengah dalam silogisme, tetapi bagi yang lainnya tidak, ini jika proposisinya bersifat empiris dan umum. Jika pun kita memerlukan term penengah, itu hanya untuk memberikan penjelasan kepada orang lain, sebagai contoh dalil akal dan naqli. Sesungguhnya term penengah tidak dipergunakan dalam sebuah proposisi, ia diperlukan hanya untuk memberikan penjelasan kepada orang lain sebagai dalil dan contoh.
b. Kritik terhadap proposisi universal dalam silogisme
Para ahli logika Aristotelan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang terpercaya benar dan yakin tidak dapat dihasilkan kecuali dengan silogisme demonstratif (al-qiyas al-burhani). Silogisme demonstratif, atau yang mereka sebut dengan silogisme yang deduktif (al-qiyas al-syumuly), adalah suatu silogisme yang proposisinya bersifat silogisme afirmatif. Pengetahuan yang terpercaray benar tidak dapat dihasilkan dari proposisi negatif atau yang terdiri dari dua proposisi partikular dalamsuatu silogisme.
Ibn Taimiyah mengatakan, apabila dalam silogisme diisyaratkan mesti ada proposisi universal, tentu ini berarti tanpanya kita tidak akan dapat memperoleh ilmu dan menghasilkan suatu kesimpulan. Kalau memang demikian halnya, tentu pengetahuan kita tentang proposisi itu semestinya badihy, aksiomatik atau mudah, dan bahkan tentunya juga pengetahuan kita tentang unsur-unsurnya---subjek dan predikat---lebih mudah lagi dari proposisi itu. Akan tetapi proposisi itu bersifat teoretis, spekulatif maka tentu ia butuh kepada proposisi yang badihy. Dengan demikian, ia merupakan lingkaran yang saling keterkaitan, atau bagaikan rantai silsilah yang tidak berkesudahan. Hal ini jelas tidak masuk akal dan absurd dengan sendirinya
Karena iyu, kata Ibn Taimiyah, sesungguhnya kita dapat saja mengetahui sebuah konklusi, tanpa harus adanya perantara dengan proposisi universal yang terdapat pada premis dalam suatu silogisme. Hal ini banyak sekali kita jumpai di dalam kenyataan. Misalnya, apabila telah diketahui satu adalah setengah dari dua, dengan mudah dapat diketahui bahwa satu (yang baru diketahui) juga mesti setengah dari dua, demikian juga satu, satu yang lainnya adalah setengah dari dua. Kesimpulannya dapat diketahui tanpa memerlukan perantara proposisi universal dan term penengah dalam suatu silogisme,[[14]] sebagaimana yang terdapat dalam logika silogisme Aristoteles.
Menurut teori para ahli logika Aristotelian untuk sampai kepada suatu kesimpulan harus dimulai dengan dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor, dan kedua premis ini dihubungkanoleh term penengah. Sistem logika seperti inilah yang dikritik oleh Ibn Taimiyah dan dianggap suatu pemikiran yang rancu dan tidak beralasan. Sebab dalam premis mayor itu sendiri sebenarnya sudah terkandung kesimpulannya dengan demikian kesimpulan yang diambil dalam satu silogisme sesungguhnya tidak mempunyai arti lagi.
c. Kritik terhadap pembahasan silogisme yang terdiri dari dua proposisi
Aristoteles dan pengikutnya dari para filosof muslim berpendapat bahwa satu silogisme yang benar hanyalah tersusun dari dua premis. Menurut Ibn Taimiyah, pendapat yang mengharuskan dalam satu silogisme hanya terdiri dari dua premis adalah pendapat yang tidak benar. Sebab, ia sangat bergantung kepada kebutuhan dalam menjelaskan suatu kesimpulan. Ada orang yang butuh kepada satu premis, ada yang butuh kepada dua premis, dan yang lain butuh kepada tiga atau empat premis. Artinya, ia sangat bergantung kepada si pembuat argumentasi. Hal ini disebabkan karena kemampuan nalar yang dimiliki oleh setiap orang, [[15]] tidaklah sama.
Proposisi kenabian (hadis-hadis nabi) umpamanya, tidak memerlukan silogisme logis. Karena ilmu-ilmu agama telah merupakan natijah (pernyataan yang tetap, konklusi) dari sabda rasul. Hadis-hadis mutawatir umpamanya, tidak dapat dikatakan bukan merupakan ilmu, walaupun tidak dihasilkan melalui silogismedemonstratif.[[16]]
Ibn Taimiyah memberikan suatu contoh fiqiyah, bahwa dengan satu premis kita dapat mengambil suatu kesimpulan dalam silogisme. Bila seseorang ingin mengetahui bahwa sesuatu yang memabukkan itu adalah diharamkan, tetapi ia belum mengetahui bahwa sesuatu ini memabukkan atau tidak, maka untuk itu, ia cukup hanya membutuhkan kepada satu premis saja, yaitu dengan mengetahui bahwa sesuatu ini adalah memabukkan. Kemudian bila dikatakan kepadanya, “ini adalah haram”, jika ditanyakan apa alasannya, jawabnya adalah, “karena ia memabukkan”. Dengan demikian terjawablah dengan sempurna apa yang dituntut.[[17]]
Ibn Taimiyah mengatakan bahwa membatasi dua premis saja dalam satu silogisme adalah pendapat yang salah dan bertentangan dengan fitrah manusia, dan membuat akal pikiran kita terjauh dari mengetahui Allah SWT dan dari ketetapan-ketetapan nabi-Nya.[[18]]
d. Kritik atas perbedaan silogisme Deduktif dan silogisme Analogis
Para ahli logika Aristotelian membedakan nilai kebenaran antara silogisme demonstratif deduktif (qiyasal-syumul) dan silogisme partikular analogis (qiyas al-tamsil). Menurut logika Aristoteles, silogisme deduktif menghasilkan kebenaran yang pasti, sedangkan silogisme analogis hanya menghasilkan kebenaran yang tidak menacapai ke tingkat benar pasti, hanya tingkat kemungkinan saja (dzanny). Sebab, silogisme deduktif adalah silogisme dalam bentuk demonstratif utama, karena ia tersusun dari dua premis dan diikuti dengan premis ketiga yang merupakan sebuah kesimpulan [[19]] yang benar pasti hasilnya.
Pendapat di atas ini, menurut Ibn Taimiyah, adalah sebuah klaim yang tidak tepat. Sebab, kedua silogisme itu deduktif atau analogis, kebenarannya adalah sama. Perbedaan tingkat kebenaran antara pasti (yaqin) dan tidak pasti (dzanny) hanya bergantung kepada materinya. Bila materi atau premisnya benar dan pasti pada silogisme partikuler analogis maka kedudukannya sama dengan silogisme demonstratif deduktif; tetapi bila salah satunya tidak benar pasti, yang lainnya juga tidak benar pasti atau hanya berupa kemungkinan benar saja (dzanny).
Ibn Taimiyah menunjukkan kesamaan benar antara silogisme demonstratif deduktif dan silogisme partikuler analogis, bila materinya adalah sama-sama benar dan pasti. Ia menjelaskan: bahwa silogisme demokratif deduktif terdiri dari tiga term: minor, penengah, dan mayor.
Silogisme analogis merupakan asal yang sesungguhnya dari silogisme deduktif, karena sesuatu yang empiris adalah menunjukkan kepada sesuatu yang nyata, real, bukan kepada hal-hal yang umum, universal. Sedangkan akal kita pertama sekali terlebih dahulu bersentuhan dengan hal-hal yang partikular dan empiris itu. Sebab, kemampuan akal bersama komulatif (al-‘aql al-musytarak) adalah terdiri dengan cara menghubungkan antara yang partikular-partikular, dan kemudian di dalam akal kita ia menjadi sebuah proposisi universal.
Karena itu dapat dipastikan, kata Ibn Taimiyah, bahwa yang universal tidak mungkin terdapat di dalam diri kita sebelum mengetahui yang partikular-partikular. Karena itu, tanya Ibn Taimiyah kepada mereka yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang yang partikular adalah lemah dalam silogisme, dan mereka tidak menyebutkan bahwa yang partikular adalah suatu kemestian sebagai dasar dalam silogisme. Orang yang menyangkal pernyataan partikular , dan mengangapnya bahwa silogisme tidak butuh kepadanya, adalah semacam keangkuhan ilmiah, kata Ibn Taimiyah.[[20]]
2. Aspek afirmatif
Di atas telah dijelaskan beberapa kritikan Ibn Taimiyah terhadap pernyaan negatif para ahli logika Aristotelian, yaitu bahwa benarnya sebuah pernyataan tidak dapat dicapai, kecuali dengan silogisme.
Pada bagian ini Ibn Taimiyah melancarkan kritikannya terhadap pernyataan mereka yang afirmatif, yaitu sebuah silogisme dapat menghasilkan ilmu bila tersusun dari pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi. Ibn Taimiyah menyadari bahwa aspek ini adalah aspek yang lebih mendasar dari aspek-aspek lainnya. Ia sebenarnya mengakui keabsahan komposisi silogisme logis.
Malahan, menurut Ibn Taimiyah, cara yang ditempuh dengan silogisme Aristoteles amat berbelit-belit dan sarat dengan kesulitan. Ia membuat akal menjadi lelah, kerja tidak efisien dan banyak omong kosong. Kalau begitu, bagaimana sesunguhnya pendapat Ibn Taimiyah karena di satu sisi ia mengatakan bahwa silogisme tidak menghasilkan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain ia tidak membantah kebenaran konklusi dari silogisme deduktif itu.
Ibn Taimiyah mengatakan bahwa para ahli logika telah membatasi ilmu hanya dengan dua cara. Pertama, konsep-konsep (tashawwurat) tidak dapat dihasilkan kecuali dengan definisi (had). Kedua, pertanyaan-pertanyaan (tashdiqat) tidak dapat dicapai kecuali dengan silogisme. Pendapat seperti ini, menurut Ibn Taimiyah tidaklah benar. Karena kalau memang pernyataan itu benar, tentu ini berarti bahwa seluruh ilmu yang benar hanyalah hasil dari dua cara itu, dan selainnya berarti tidak benar. Pendapat inilah yang dibantahkan Ibn Taimiyah.[[21]] Berikut ini adalah beberapa kritikannya terhadapa aspek afirmatif :
a. Silogisme tidak berpengaruh terhadap ilmu
Logika aristoteles yang dikenal dengan logika formal, menurut Ibn Taimiyah tidak memberikan kegunaan terhadap ilmu pengetahuan; bahkan hanya mendatangkan kesulitan. Apa yang dapat diketahui dengan silogisme logis, sebenarnya dapat diketahui tanpanya. Sedangkan apa yang dapat diketahui tanpa silogisme tidak dapat diketahui dengan silogisme.
Silogisme sama sekali tidak bernilai guna bagi ilmu, baik ilmu yang sudah dihasilkan ataupun yang akan. Sebab, silogisme tidak dapat mengahasilkan ilmu yang belum diketahui (majhul), sedangkan ilmu yang sudah diketahui (ma’lum) juga tidak membutuhkannya. Silogisme hanyalah pekerjaan sia-sia, kata Ibn Taimiyah karena di samping tidak bernilai guna dalam menghasilkan ilmu juga tidak dapat menghasilkan ilm baru.
b. Silogisme logis tidak efektif
Menurut Ibn Taimiyah, jika dalil dan demonstrasi adalah petunjuk dan cara untuk memperoleh ilmu, maka silogisme merupakan kendala untuk sampai kepada ilmu. Untuk sampai kepada sebuah kesimpulan metode silogisme menempuh jalan yang berbelit-belit dan tidak efeketif. Ibn Taimiyah memberikan sebuah perumpamaan, seperti seorang musafir yang bepergian menuju Makkah atau negeri lainnya; ia lalu mengambil jalan yang tidak lurus, yang tidak dikenal, akhirnya ia sampai juga di negeri yang ditujunya dalam waktu yang sangat lama dengan tenaga yang amat lelah, ataupun ia bisa saja tidak sampai ke tujuan. Perjalanan yang melelahkan, sulit dan tidak efisien untuk sampai tujuan itu ialah logika silogisme karena untuk masuk ke suatu kesimpulan, harus didahului dengan menyusun sebuah proposisi-proposisi dan untuk penyusunan proposisi harus didahului pula dengan pengetahuan bagian-bagiannya, yaitu subjek dan predikat, subjek dan predikat merupakan term-term harus diketahui pula dulu dengan definisi, dan untuk membuat definisi harus memahami syarat-syarat tertentu pula yang amat sulit memenuhinya. Begitulah para ahli logika, kata Ibn Taimiyah.
c. Silogisme logis tidak fitri (instingtif)
Menurut Ibn Taimiya Ibn Taimiyah, silogisme yang benar ialah yang bersifat fitri alami yang inheren pada diri kita, dan tidak membutuhkan kepada penyusunan silogisme logis. [[22]] Bila hal yang yang fitri dan alami ditempuh dengan cara tidak fitri dan alami, ia akan menimbulkan suatu kesulitan dan penyiksaan terhadap diri sendiri dan tidak akan berhasil guna. Jalan pendek dan efisien untuk sampai kepada ilmu yang benar adalah dengan cara melalui jalan yang fitri dan alami. Sedangkan silogisme telah menjadikan jalan yang berbelit-belit untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dalam ilmu penegtahuan.[[23]]
Karena itu, sebagaimana telah disebutkan pada aspek negatif, Ibn Taimiyah tidak mementingkan adanya dua premis dalam sebuah dalil (silogisme). Silogisme bisa saja terdiri dari satu premis atau lebih banyak. Artinya tidak ada ketentuan yang pasti dan baku pada setiap orang pada sesuatu yang ingin dicapai. Ia berbeda dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan nalar seseorang.
d. Kesimpulan dapat diketahui tanpa silogisme
Menurut Ibn Taimiyah, kita dapat saa memperoleh kesimpulan tana silogisme, dan cukup dengan hukum kelaziman yang fitri. Umpamanya, kita mengetahui bahwa sesuatu ini adlah lazim bagi itu, maka berarti yang dilazimi (akibat) berdasarkan kepada yang lazim (sebab); sekalipun yang dilazimi tidak dinyatakan secara langsung dan eksplisit. Umpamanya dalam firman Tuhan :
÷Pr& (#qà)Î=äz ô`ÏB ÎŽöxî >äóÓx« ÷Pr& ãNèd šcqà)Î=»y‚ø9$# ÇÌÎÈ
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri) ? (al-Thuur, [52]:35).
Ayat diungkapkan dalam bentuk pertanyaan retorika menyangkal (al-istifham al-inkary), menjelaskan bahwa proposisinya sendiri telah merupakan dalil yang fitri, aksiomatik, dan inheren di dalam diri kita sendiri, tidak mungkin seseorang pun akan menyangkal. Sedangkan eksplisit, ayat memang tidak menyatakan tentang wujud Allah, tetapi dengan analogi logis ayat mengandung makna adanya wujud Tuhan.
e. Silogisme tidak bermanfaat terhadap ilmu partikular
Ilmu partikular (juz’iyat) lebih mudah mengetahui dari silogis logis dan ia lebih jelas serta dapat diketahui tanpa silogisme Aristoteles. Artinya, pengetahuan, menurut Ibn Taimiyah, sangat bertumpu pada persoalan-persoalan partikular, induktif, dan yang partikular pun tidak dapat menghasilkan kesimpulan pengetahuan yang universal karena sebuah kesimpulan hanya dapat diambil dengan silogisme analogis (qiyas tamtsil), yaitu dengan menganalogikan sebuah partikular yang sudah diketahui kepada yang partikular lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa demonstrasi tidak menghasilkan penegtahuan positif apa pun tentang wujud, baik secara umum atau khusus, universal ataupun partikular.
f. Silogisme yang sesungguhnya adalah yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya
Bagaimanapun, kata Ibn Taimiyah, logika hanyalah kesepakatan manusia dan selalu terbuka bagi setiap kekeliruan dan kesalahan, baik pada metode ataupun pada seperangkat alat yang bersifat manusiawi. Makanya, tak pelak lagi, kata Ibn Taimiyah, bahwa ia lebih rendah daripada metode yang sudah pasti yang terdapat dalam Al Quran dan al-Sunnah, ke mana setipa mukmin wajib berpegang teguh, dan mengesampingkan segala sesuatu selainnya.[[24]]
Menurut Ibn Taimiyah, para rasul adalah pemberi petunjuk dan pembimbing bagi manusia untuk mengetahui keadilan (al-adl) dan mengajarkan timbangan (qiyas) yang benar bagi akal, yang berdasarkan kepada ajaran agama. Adalah dugaan yang keliru, kata Ibn Taimiyah, bahwa ilmu kenabian hanya sebatas pernyataan atau berita saja, dan tidak mencakup ilmu-ilmu rasional (al-‘ulum al-‘aqliyah). Padahal ilmu yang sesungguhnya benar adalah ilmu yang berasal dari para nabi dan dari Nabi Muhammad SAW serta para pewaris beliau karena ini bersumber dari Allah SWT.
Menurut Ibn Taimiyah, silogisme logis dan silogisme analogis memang sma-sama terpakai dalam al Quran dan al-Sunnah, hanya saja silogisme analogis lebih baik dan sempurna, serta lebih praktis, karena ia lebih cocok dengan fitrah manusia. Berikut firman Allah :
ª!$# ü“Ï%©!$# tAt“Rr& |=»tGÅ3ø9$# Èd,ptø:$$Î/ tb#u”ÏJø9$#ur 3 $tBur y7ƒÍ‘ô‰ãƒ ¨@yès9 sptã$¡¡9$# Ò=ƒÌs% ÇÊÐÈ
Allah lah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca (al-Syura, [42]:17)
Jadi, mizan atau neraca, menurut Ibn Taimiyah, adalah keadilan untuk menimbang sesuatu; ia adalah qiyas analogis qurani yang diwahyukan; yang dengannya kita dapat mengetahui benar atau salahnya akal pikiran, bahkan dengannya kita dapat menimbang segala sesuatu yang bersifat umum, yang empiris ataupun yang rasional.
g. Ilmu agama adalah ilmu yang paling sempurna
Bagi Ibn Taimiyah, kekuatan akal hanya berfungsi untuk membenarkan dan tunduk kepada nash. Akal hanya menjadi saksi pembenaran dan penjelasan dalil-dalil al-Quran, bukan menjadi hakim yang akan mengadili dan menolaknya. Akal harus diletakkan di belakang nash-nash agama da tidak boleh berdiri sendiri. Jika dalam bidang empiris saja daya kerja akal manusia mempunyai keternbatasan, apalagi dalam bidang metafisika dan alam gaib, ia akan bisa tersesat apabila berdiri sendiri dan tidak mendapat bimbingan karenanya, akal harus tunduk kepada wahyu.[[25]]
Ibn Taimiyah mendasarkan pembuktian atas qiyas analogi qurani. Ia mengemukakan dua bentuk analogi qurani, yaitu : ayat-ayat (al-ayat) dan analogi aula (promordial, utama). Kedua bentuk pembuktian ini merupakan segi-segi konstruktif positif dari logika Ibn Taimiyah
1). Ayat adalah ilmu tentang sesuatu tanda yang tertentu, yang mengacu kepada objek tertentu dari tanda itu sendiri. Cara seperti itu, menurut Ibn Taimiyah, adalah lebih teliti dan lebih dekat kepada fitrah manusia daripada silogisme logis Aristoteles. Sebab, silogisme logis Aristoteles memastikan kepada akal pikiran untuk melakukan pengkajian kepada setiap partikular yang terdapat pada proposisi universal, kemudian menjadikan setiap individudari partikular megeneralisasikan menjadi hukum yang sama, universal. Ini diperlukan, untuk merealisasikan keabsahan proposisi universal. Cara ini, menurut Ibn Taimiyah, sangat sulit dan tidak sesuai dengan fitrah manusia yang alami.[[26]]
2). Analogis utama atau qiyas aula adalah perbandingan antara sesuatu dengan sesuatut yang lebih sempurnadarinya. Adanya qiyas aula karena terdapatnya kesamaan pada jenis lafadz atau ungkapan, tapi berbeda dari segi makna atau pengertian yang diacu oleh ungkapan itu. Bagi Ibn Taimiyah, untuk menyatakan analogi kesempurnakan, kesempurnaan bagi Allah mesti memenuhi dua ketentuan. Pertama, bahwa kesempurnaan itu adalah hal yang mungkin pada diri-Nya, bukan sesuatu hal yang mustahil. Kedua, tidak mengandungsuatu kekurangan dalam bentuk apapun , atau persamaan dengan selain-Nya.[[27]]
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari paparan makalah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:
- Silogisme adalah jenis argumen logis di mana satu proposisi (kesimpulan) yang disimpulkan dari dua orang lain (tempat) dari suatu bentuk tertentu, yaitu kategori proposisi.
- Silogisme terbagi menjadi
v Kategorik
Silogisme Katagorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan katagorik.Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan dengan premis mayor (premis yang termnya menjadi predikat), dan premis minor (premis yang termnya menjadi subjek).Yang menghubungkan diantara kedua premis tersebut adalah term penengah (middle term).
v Hipotesis
Adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi katagorik.
v Disjungtif.
Silogisme disyungtif dalam arti luas premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif.
- Pemanfaatan silogisme dalam kehidupan keseharian bisa dilakukan sebagai uapaya untuk menimbang berbagai peristiwa hokum atau yang lainnya secara obyektif, sehingga menghasilkan temuan yang analitik, obyektif dan empirik.
- Memahami Pola Penalaran
Ibn Taimiyah mengatakan bahwa para ahli logika telah membatasi ilmu hanya dengan dua cara. Pertama, konsep-konsep (tashawwurat) tidak dapat dihasilkan kecuali dengan definisi (had). Kedua, pertanyaan-pertanyaan (tashdiqat) tidak dapat dicapai kecuali dengan silogisme. Pendapat seperti ini, menurut Ibn Taimiyah tidaklah benar. Karena kalau memang pernyataan itu benar, tentu ini berarti bahwa seluruh ilmu yang benar hanyalah hasil dari dua cara itu, dan selainnya berarti tidak benar. Berikut kritikan Ibn Taimiyah terhadap silogisme :
a. Silogisme tidak berpengaruh terhadap ilmu
b. Silogisme logis tidak efektif
c. Silogisme logis tidak fitri (instingtif)
d. Kesimpulan dapat diketahui tanpa silogisme
e. Silogisme tidak bermanfaat terhadap ilmu partikular
f. Silogisme yang sesungguhnya adalah yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya
g. Ilmu agama adalah ilmu yang paling sempurna
DAFTAR PUSTAKA
Kamal, Zainun.2006.Ibn Taimiyah Versus Para Filosof.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
Soleh, Khudori,A.2010.Integrasi Agama & filsafat.Malang:Uin-Maliki Press (Aanggota IKAPI).
Arikunto, Suharsimi, dkk. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
From: “SONYMAN” <sonyman@uk2.net>To: “Is-Lam@Isnet.Org” <is-lam@isnet.org> Date: Thu, 8 Jun 2000 16:56:05 +0700
http://aristobe74.blogspot.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Proposition-Silogisme/
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat-Silogisme/
http://www.halimsani.wordpress.com / 2007 / 09 / 18 / apakah-filsafat-itu-sebuah-pengantar-kealam-filsafat/
http://www.unhas.ac.id / ~rhiza / mystudents / filsafat – iptek / Bab % 209 % 20 Yunus % 20 dan % 20 Halidin.ppt
Lanur, Alex. 1983. Logika Selayang Pandang. Yogyakarta: Kanisius.
Mundiri. 1994.Logika. Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution Hakim, Andi. 2005. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
[2] Al-jabiri,Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi,1991),385 dan seterusnya.
[13] Ibn Taimiyah,Ibid,hlm.89;Al-Nasysyar,Op.cit.,hlm.181;Muhammad Husny al-zain,Op.Cit.,hlm.96
[15] Ibn Taimiyah, Op. Cit.,hlm.110; Al-Suyuthy, Op. Cit., hlm.224-225; al-Nasyasyar, Op. Cit.,hlm 182
[17] Ibn Taimiyah,Ibid., hlm.168;Al-suyuthy, Op. Cit., hlm. 266;Muhammad Abd al-Sattar, Op. Cit., hlm.383
[18] Ibn Taimiyah,Muwafaqah Shahih al-Manqul li Sharih al-Ma’qul,(kairo: al-Sunnah Muhammadiyah,1951), jilid 3.,hlm.65;Muhammad Husny al-Zain, Op. Cit.,hlm.103
[19] S.A. kamali, Ibid.,hlm 79
[20] Ibn Taimiyah, Ibd., hlm.117; Muhammad Husny al-Zain, Op. Cit., hlm.147.
[25] Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah,(Kairo Dar al-Fikr al-Araby, tt),jilid 1, hlm.214
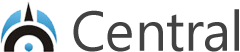










No comments:
Post a Comment